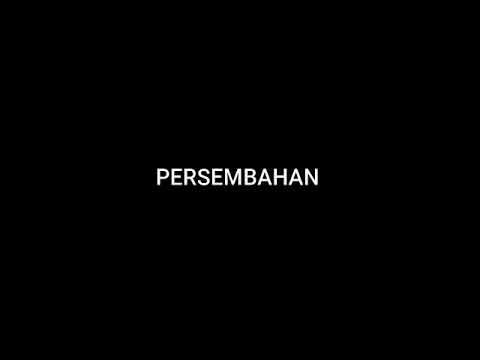Lagu ini dipersembahkan oleh: VG EUPHEMIA UNJ & BATAVIA CHAMBER ORCHESTRA Lagu/lirik: Rien Safrina, M.A., Ph.D Aransemen Musik: R.M. Aditya Andriyanto, S.Pd., M.Sn. Tata Suara: Alfrinda Clara, S.Pd. Editor Audio/Video: R.M. Aditya Andriyanto/Rizky Fauzy Ananda
EDURA UNJ UNTUK DIES NATALIS UNJ KE-56
EDURA UNJ sebagai university business center berperan aktif dalam mengembangkan potensi seluruh civitas akademika. Dalam bidang keolahragaan, unit bisnis ini memiliki misi pendidikan di setiap cabang olah raga, event kejuaraan tingkat pelajar, dan menyalurkan pelatihan professional. Dalam bidang media, ada UNJ PRESS yang menerbitkan buku berkualitas karya dosen, mahasiswa, dan pihak eksternal. Di hari jadi UNJ yang ke-56 , EDURA UNJ berkomitmen memberikan yang terbaik untuk kemajuan universitas
Hymne Universitas Negeri Jakarta
Hymne Universitas Negeri Jakarta
Karya: Drs. M. Soeharto
Paduan Suara Universitas Negeri Jakarta & Batavia Chamber Orchestra
Guru Penuhilah Rumah dengan Buku
“Kita meyakini mentalitas suatu bangsa ada di tangan guru. Mentalitas yang dibentuk dari imaji buku-buku yang guru baca. Guru-guru kita jangan sampai terpenjara imajinasinya hanya karena tak berbuku. Kita mendapati guru yang bergaji tapi enggan membeli buku-buku. Oh guru…..“
November lalu saya bertemu dengan Romo Mudji. Saat itu Romo Mudji sedang duduk-duduk di ruang tunggu kuliah Pasca Sarjana Universitas Negeri Jakarta (UNJ). Dengan Romo Mudji saya pun mengobrol mengenai sejarah, pendidikan, buku, budaya tulis-menulis dan lain sebagainya. Satu hal yang tak lepas saat bertemu Romo Mudji adalah peristiwa berbagi buku.
Saat ngobrol santai itu, Romo berbicara mengenai pemaknaan ulang mengenai hari guru. Saya pun berujar mengenai ingatan guru yang tak lagi berumah buku. Ingatan-ingatan guru tak berumah buku itu adalah ingatan generasi kami yakni generasi digital. Dalam ingatan kami mengenai guru adalah mereka yang bermobil dan bermotor dan bergadget. Di rumahnya, guru yang kita ingat adalah televisi bukan buku-buku. Ingatan itu berdasarkan obrolan dan diskusi dengan mahasiswa-mahasiswa baru yang tergabung dalam Lembaga Kajian Mahasiswa UNJ. Saya pun berucap kepada Romo, “Mungkin itu ingatan kami mengenai guru-guru yang di kota”
Romo Mudji mengajak saya untuk mendiskusikan mengenai ingatan guru itu dengan mahasiswa S3 Pascasarjana UNJ. Kebetulan Romo memang mengajar filsafat pendidikan dan kebudayaan di Pascasarjana UNJ. Mengapa obrolan ringan mengenai ingatan guru ini menjadi penting? “Ini terkait dengan proses konsientisasi (penyadaran) mengenai pendidikan dan kebudayaan,” kata Romo.
Guru pantas diingat dan dikenang. Romo Mudji berujar mengenai pemaknaan guru bermula dari ingatannya mengenai guru-guru di masa silam. Kini kita mendapati penghormatan guru melalui sertifikasi yang klise. Oleh karena itu kita akan mendapati guru profesional dan guru kebudayaan. Yang pertama adalah guru yang dihasilkan dari proses serangkaian pengumpulan sertifikat, tes, pengujian, dan penilaian. Yang kedua adalah guru yang sudi ikhlas mengajar berbagi pengetahuan dengan “membaca” dengan hati melalui serangkaian peristiwa pemaknaan hidup.
Bagi Romo Mudji ingatan mengenai guru kebudayaan adalah ketika ia mengingat masa kecilnya naik turun tangga di Borobudur. Di sana ada guru yang sudi mengingatkan kepadanya mengenai pembacaan makna relief-relief di batu-batu dan pemaknaan perjalanan Sidharta Gautama. Cerita dan kisah itu dicatat dan membekas melalui ingatan.
Kini ingatan berbeda tentang guru bagi kami sebagai generasi digital yang menganggap guru adalah yang mengajak kita untuk membaca dengan cara merekam dan berfoto melalui serangkaian kegiatan bernama “Study Tour”. Lalu dibekukan lewat Instagram, Facebook dan Twitter. Kini ingatan guru yang dirasakan Romo Mudji sebagai guru kebudayaan semakin menghilang.
Di Abad 21 Kita mengingat guru profesional yang masih terbelenggu dengan gaya dan metode dalam mengajar. Ingatan mengenai guru-guru profesional kita hari ini adalah guru yang tak berumah buku. Guru kita yang disibukan dengan pengejaran sertifikasi, cap, silabus, dan juga RPP.
Guru-guru kita akan memadati seminar-seminar hanya demi selembar sertifikat. Sertifikat yang dibutuhkan demi pemberkasan. Sehingga guru kita disibukan dengan formulir dan penghambaan terhadap gaji. Dalam kacamata profesionalitas itu kita mendapati guru yang hebat adalah guru yang lulus ujian kompetensi atau yang disebut dengan Uji Kompetisi Guru (UKG).
Guru Berbuku
Kisah guru hari ini adalah cerita mengenai guru honorer yang belum dibayar gajinya. Di koran-koran kita masih mendapati guru-guru yang berdemo untuk disegerakan menjadi PNS. Miris sekali ada oknum yang menjual buku-buku yang ada di perpustakaan untuk diloakan, dibuang dan dilebur. Di abad 21 guru hidup di mana buku tak lagi menjadi bacaan mulia. Membeli buku tak pernah menjadi prioritas dalam hidup di tengah sibuknya berkredit mobil dan motor.
Kita jarang mendapati guru yang berbuku. Membaca banyak buku dan berkisah kepada murid-muridnya. Mengajak muridnya menyelami makna hidup dengan kisah-kisah dari buku-buku. Mengajak muridnya ke toko buku. Memaknai peristiwa membeli buku menjadi penting sebagai pengembangan imajiinasi. Kita kesulitan berimaji guru yang mau memenuhi rumahnya dengan buku. Kita jarang mendapati guru mengajak muridnya main ke rumah mengobrolkan buku.
Di koran-koran kita hari ini, ingatan tentang guru adalah adalah upacara penghormatan guru melalui ‘Simposium Guru’ yang dihadiri oleh Jokowi dan Anies Baswedan nan megah. Sekaligus penghadiahan guru-guru berprestasi melalui selembar sertifikat. Semakin bersedih dan pilu jika kita jika penghormatan hari guru seperti ini.
Di hari guru sekolah-sekolah guru berupacara memperingati guru. Kita jarang mendapati guru berupacara sunyi dengan buku-buku di rumahnya. Ketika kita masuk ke rumah guru, kita hanya mengingat televisi, kulkas, dan kipas angin. Kita merindukan guru yang mengisi rumahnya dengan buku-buku. Kita rindu bergurau sambil berdiskusi mengenai buku di rumah guru yang berbuku. Kita jarang diajak bermesraan dengan buku-buku di rumah guru yang berbuku.
Kita meyakini mentalitas suatu bangsa ada di tangan guru. Mentalitas yang dibentuk dari imaji buku-buku yang guru baca. Guru-guru kita jangan sampai terpenjara imajinasinya hanya karena tak berbuku. Kita mendapati guru yang bergaji tapi enggan membeli buku-buku. Oh guru…..
Concern Building Of Education (2)
Pesan Edukasi “Laskar Pelangi”
“Bermimpilah, maka Tuhan akan memeluk mimpi-mimpimu,”
Menurut analisa semiotik penulis terhadap kisah “Laskar Pelangi”, didapat suatu pesan bahwa pendidikan adalah hak mutlak warga masyarakat. Dengan latar pedalaman daerah terpencil, mimpi besar seorang siswa dapat terwujud. Hal inilah yang mungkin menjadi ihwal menyikapi keterbatasan menjadi hal yang menggugah semangat belajar. Penulis lebih sepaham bila kita mengistilahkannya sebagai wishfull thingking, artinya bahwa geliat pendidikan nusantara nantinya berangkat dari pelosok daerah pedalaman yang dengan keterbatasannya dapat memaksimalkan cita.
Kemunculan kisah “Laskar Pelangi” juga dapat dikatakan sebagai kritik bagi pemerintah. Terutama masalah perhatiannya terhadap pembangunan pendidikan di daerah pelosok. Hal yang memancing perhatian publik adalah bahwa sebenarnya kisah “Laskar Pelangi” adalah potret sesungguhnya tentang sikap apatisme pemerintah dalam akses pemerataan dan kualitas pendidikan. Ada pesan edukasi dalam kisah tokoh tersebut, Seperti, Ikal selaku tokoh utama yang kental dengan cita dan mimpi, Lintang yang jenius, Mahar yang artistik, Ibu Muslimah (Cut Mini) yang begitu komitmen terhadap pendidikan, serta Pak Arfan yang begitu setia pada sekolah mereka. Penjaga moral yang tak pernah surut semangatnya mengurus sekolah yang hanya bermuridkan sepuluh orang, meski tanpa keuntungan sepeserpun. “Hiduplah untuk memberi sebanyak-banyaknya, bukan untuk menerima sebanyak-banyaknya,” demikian lelaki renta itu menyemangati Laskar Pelangi.
Hal yang menarik dari kisah ini yaitu tidak meninggalkan tema sentral pendidikan, sebagaimana dinarasikan oleh Andrea. Kisah Laskar Pelangi, memberikan inspirasi bagi penonton dan pembaca betapa pentingnya pendidikan. Sosok Lintang yang jenius adalah potret buram pendidikan kita. Kisah ini memahamkan kita kalau di negeri ini pendidikan masih seperti menara gading yang harus di nomor duakan demi menafkahi keluarga. Minggatnya Lintang dari sekolah mereka membuktikan bahwa untuk sekolah di negeri ini tidak cukup hanya dengan semangat dan kecerdasan otak, unsur materi masih menjadi syarat utama. Di usianya yang masih belia ia dipaksa menanggung beban hidup yang belum seharusnya ia pikul. Bekerja menafkahi keluarga dan meninggalkan bangku sekolah.
Dalam Kisah ini pun dipesankan bahwa kecerdasan tidak diukur dengan nilai-nilai angka dan materi semata, tapi dengan hati, kata Pak Arfan. Bahwa memang arti kata hati terdapat pesan humanistik. Dimana pendidikan dilakukan untuk memanusiakan manusia. Membangun masyarakat cerdas untuk merencanakan kehidupan di masa depan. Kebhinekaan siswa dengan latar yang berbeda mengisi setiap kegiatan pendidikan dan kemudian menjadi kunci, bahwa pendidikan adalah perwujudan realita yang harus dijalani dengan kesabaran, keikhlasan, dan kesungguhan. Hadirnya sosok Mahar dalam film ini, setidaknya memberikan sudut pandang lain tentang paradigma kecerdasan. Bahwa bukan hanya Lintang yang cerdas, Mahar yang suka musik pun juga dapat dikatakan cerdas. Dimitri Mahayana menyebutnya sebagai Multi Intelegent.
Concern Building Of Education (1)
“Laskar Pelangi” Kebangkitan Pendidikan Di Daerah Pedalaman
Bila pemerataan akses pendidikan terwujud, pondasi pembangunan akan berjalan aktif bersama kesadaran masyarakat untuk selalu belajar dan mewujudkan pendidikan dari semua (education from all) sampai terbentuk kemandirian berkarakter.
(HI)
Indonesia adalah Negara besar yang berpenduduk lebih dari 220 juta jiwa dengan wilayah yang terdiri 13.000 pulau. Kebhinekaan yang terdiri 300 suku bangsa, dengan 200 bahasa yang berbeda. Begitu luas dan kaya negeri ini terhampar, bahkan dengan kesuburan tanah Indonesia analogi kayu dan batu saja bisa jadi tanaman. Belum lagi hutan dan kekayaan bahari yang melimpah, sampai-sampai kita lengah menjaga dan melindunginya. Di sisi lain Hal terpenting yang harus diingat adalah dalam setiap jengkal kekayaan, kedaulatan, kebhinekaan bangsa Indonesia ada hak yang harus dipenuhi, yaitu pendidikan untuk semua (education for all). Dimana kemanusiaan dijunjung, hak asasi dihargai, dan keadilan di wujudkan. Pendidikan mengambil peran penting dalam membangun kehidupan berbangsa saat ini.
Salah satu hal yang menjadi ironi dunia pendidikan saat ini adalah masalah pemerataan akses dan kualitas pendidikan di Indonesia yang belum signifikan. Dari Laporan UNDP menunjukkan angka Human Development Indeks (HDI) masyarakat Indonesia yang menjadi salah satu indikator pemerataan pendidikan di Indonesia jauh tertinggal dari negara-negara lain di Asia. Angka putus sekolah masih tinggi, Menurut data resmi yang dihimpun dari 33 Kantor Komnas Perlindungan Anak (PA) di 33 provinsi, jumlah anak putus sekolah pada tahun 2007 sudah mencapai 11,7 juta jiwa. Terjadi penambahan tahun ini, mengingat keadaan ekonomi nasional yang kian memburuk, dan tingkat kemiskinan yang terus bertambah kurang lebih 25% dari jumlah penduduk Indonesia.
Peningkatan jumlah anak putus sekolah di Indonesia sangat tinggi. Pada tahun 2006 jumlahnya “masih” sekitar 9,7 juta anak, namun setahun kemudian sudah bertambah sekitar 20% menjadi 11,7 juta jiwa. Dapat dibayangkan, gairah belajar dan harapan 12 juta anak Indonesia terpaksa dipadamkan. Angka putus sekolah tersebut merupakan bukti apatis pemerintah terhadap dunia pendidikan. Berkaitan dengan hal itu sebenarnya dapat diatasi, bahwa pemenuhan anggaran pendidikan 20% sebagaimana diamanatkan pada pasal 31 ayat 4 UUD (Amandemen Keempat) harus dikelola dengan baik sesuai kebutuhan.
Belum lagi nasib pendidikan didaerah pedalaman. Di Nabire dan Manokwari, Papua. Terdapat kejadian, Akibat runtuhnya gedung sekolah yang tidak layak, siswa menjadi trauma untuk duduk dan belajar kembali di sekolah. Lain halnya dengan di Palas, fasilitas pendidikan dan kulitas guru yang terbatas telah mengubur impian dan cita-cita mereka untuk mengenyam pendidikan yang berkualitas. Di Singkawang, Kalimantan barat. Siswa dihadapkan dengan keterbatasan daerah yang masih semak belukar, dan juga persepsi yang mengklaim bahwa pendidikan tidak penting. Tidak jauh berbeda dengan apa yang dialami dengan realita “Laskar Pelangi”, dengan keterbatasan pendidikan mereka berjuang mewujudkan mimpi mengenyam pendidikan
Di sisi lain, menurut F.D. Rosevelt bahwa dalam “New Deal”, Sekolah merupakan hak yang menyeluruh. Artinya, setiap orang berhak atas pendidikan yang layak sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945. Pembangunan pendidikan merupakan salah satu prioritas utama dalam agenda pembangunan nasional. Selain itu, pendidikan juga memegang peran yang signifikan dalam mencapai kemajuan di berbagai bidang kehidupan: sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Dengan pendidikan sebuah bangsa bisa bermartabat, mandiri, dan kompetitif.